TEORI TEORI
DALAM ANTROPOLOGI
Makalah
Disusun untuk memenuhi tugas :
Mata
kuliah : Antropologi
Dosen
Pengampu : Dra.Hj. Misbah Zulfa
Elisabeth
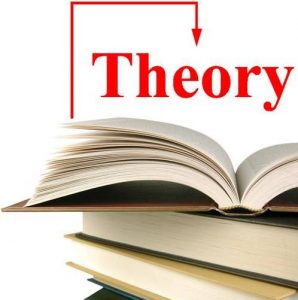
Disusun Oleh :
1. Dwi
cahyaninggrum 1401026040
2. Ilham
fatoni 1401026046
3. Safana intani
1401026054
4. Dika
aldiah
1401026062
5. Wardah
hamra 1401026073
6. Arifatun
naimah 1401026076
7. Aditya
afrianto 1401026078
FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI
INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO
2014
I.
PENDAHULUAN
Telah lama manusia
tertarik pada kebiasaan-kebiasaan dari manusia lainnya. Namun, lebih kurang 100
tahun terakhir ini, studi tentang kebudayaan manusia diterapkan sedemikian
rupa,sehingga study ini dapat disebut study ilmiah. Sejak 100 tahun yang lampau, para peminat
mengenai kebudayaan dan masyarakat lain, menjadi sadar jika mereka harus
mempelajari pokok perhatiannya menurut cara yang telah di lakukan oleh
ilmuan-ilmuan di bidang ilmu lainnya. Yaitu dengan cara yang sistematis dan
melalui observasi yang tidak berat sebelah. Untuk menggambarkan kebudayaan
secara lebih tepat dan
benar.Para ahli antropologi mulai hidup di tengah masyarakat yang di
pelajarinya, sehingga meraka dapat melakukan pengamatan bahkan dapat ikut ambil
bagian dalam kejadian-kejadian penting dari masyarakat yang bersangkutan.Juga
secara cermat mereka dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada wakil
penduduk asli atau pribumi tentang kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat mereka.
Dengan kata lain, para ahli antropologi mulai melaksanakan penelitian lapangan.
Pembicaraan meliputi
definisi antopologi sebagai disiplin yang mencari pemahaman “ perspektif ”
pelaku budaya dan pelaku ini lah yang di anggap sebagai pemilik “teori” atau
“pengetahuan” Konsep lokal knowledge akan di jadikan titik tolak pembahasan.[1]
II.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apasajakah yang dibahas dalam kajian antropologi ?
b.
Difusionisme
c.
Fungsionalisme
d.
Fungsionalisme-struktural
e.
Struktural
f.
Etnosains
g.
Simbolik
h.
Interprentivisme
i.
Postemodernisme
III.
PEMBAHASAN
A. Evoliusionisme
Pemikiran dasar evolisionisme adalah bahwa ada suatu kepastian
dalam tata tetib perkembangan, yang melintasi kebudayaan dengan kecepatan yang
agak kecil agak besar (Baal,1988; 114). Misalkan saja dalam bidang perkawinan,
Edward Watermarck bahwa ada hubungan analogis antara hewan dan manusia.Khususnya
pada jenis burung, telah ada pemilihan keturunan, bahkan burung jantan juga
memelihara anak-anaknya. Hal ini mengidentifikasiakan
bahwa masa silam perkawinan manusia pun tidak tidak campur aduk, malinkan telah
ada proses yang beradap. Perkawinan masa lalau telah berlangsung lama, telah
memikirkan hubungan seksual, dan karenanya
memerlukan perawatan.Perkawinan besar kemungkinananya berupa warisan.
Homo sapiens, aslinya juga pemakan
buah, seperti juga manusia kera tadinya hidup dalam kelompok-kelompok kecil.Jika
mereka berpencar lalu terjadi perkawinan campur aduk, sebenarnya merupakan
mitos manusia purba saja.Seperi hanya penemuan masyarakat Andaman, bahwa suatu
pasangan bercerai untuk mencuri patner baru, setelah mereka disapi.Ternyata
penelitian menunjukkan, orang Andaman suami-istri yang sangat setia. Tentu saja proses semacam ini bergerak sedikit demi sedikit
seiiring dengan perkembangan budaya mereka.
Adanya anggapan bahwa masa purba telah terjadi promiskuitas (kawin
campur aduk) tidak selamanya benar, meskipun ada tanda-tanda yang tampak kerah
itu, seperti pria lebih banyak cemburu dan terjadi poliandri, hal ini mungkin
terjadi beberapa kali saja. Begitu pula tentang hubungan kelamin sebelum
perkawinan dan konsep jusprimae noctis (hak malam pertama), yang telah
dipraktekan pada masa feodal melalui kekuasaan dan perkosaan, masih perlu
dikaji lebih lanjut. Karena, dengan
adanya etika perkawinan yang mengikat mereka tentu lambat laun proses cultural
semacam itu telah berubah.
Pandangan tentang ketakutan hubungan seks dalam keluarga antara
ayah dan anak gadisnya dan larangan perkawinan semasa saudra pria dan wanita
(incest), juga penting dalam teori evolusionisme. Masalah ini, jika dilakukan
jelas akan melanggar hukum alam dan kodrat manusia. Budaya semacam ini jelas tidak
dibenarkan karena akan ada akibat-akibat tertentu yang kurang menyenagkan.
Penelitian evolusi di Indonesia, dapat mengambil objek tentang
perkawinan tentang salah satu marga, hubungan kekerabatan religi dan
sebagainya.Misalkan saja, penelitian dapat menitik beratkan peranan mas kawin
yang pada awalnya berfungsi sebagai alat untuk perdamaian selah ada kawin lari.
Penelitian juga dapat mengkaji masalah religiusitas sejah ada pengaruh hindu
jawa adanya abangan, santri, priyai, aliran kepercayaan, dan sebagainya.
Penelitian
terakhir ini dapat memanfaatkan teori evolusi E. B. Tayor tentang
religi.Menurutnya, hubungan jiwa dengan jasmani pada saat tidur atau pingsan
tetap ada.Hanya apabila manusia telah mati, terputuslah hubungan jiwa dan
jasmani.Jiwa yang telepas dari jasmani itu dapat berbuat sekehendaknya. Alam semesta akan penuh dengan jiwa bebas tersebut, yang tidak lagi
disebut soul (jiwa) melainkan spirit (roh halus). Jika manusia menghormati roh
tersebut dengan jalan persembahyangan disebut pahanm animism.
Terjadinya
kepercayaan seperti itu karena adanya konsep survivals.Artinya, sisa–sisa
kebudayaan sebelumnya yang masih dilestarikan pada masa kebudayaan
baru.Survival ini mungkin sekalihanya berupa motif-motif spiritual, dongeng,
permainan, benda keramat dan sebagainya.Tentu saja, studi evolusi budaya
manusia tidak terbatas pada masa lalu saja, melainkan bisa diterapkan pada masa
kini.Namun, studi evolusi budaya masa kini mustinya telah berubah menjadi
penelitian perubahan budaya yang cabangnya telah amat beragam. Oleh karerna itu, perubahan budaya dapat
melalui berbagai segi dan cara yang unik. Maka dari itu, evolusi semakin kurang
diminati oleh pengkaji budaya masa kini.Selanjutnya, ketika evolusi mengalami
kemunduran, muncul difusi budaya. Yakni, sebuah kajian tentang proses
pengadopsian atau peminjaman budaya dari satu wilayah ke wilayah lain
B. Difusionisme
Difusi adalah salah satu bentuk penyebaran unsur-unsur
kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada akhir abad ke-19 dan awal
abad ke-20, ketika teori evolusi kebudayaan dari Tylor dan Morgan masih
populer, aliran difusi mulai mempengaruhi ahli antropologi dari berbagai tempat
dunia. Dua aliran utama yang mempunyai pandangan difusi dari aliran Inggris dan
aliran Jerman-Austria.[2]
Aliran difusi Inggris
adalah G. Elliot Smith. William J. Perry dan W.H.R., mereka berpendapat bahwa evolusi yang sejajar
atau pararel yang berlangsung terpisah dari sesuatu unsur kebudayaan di dua
daerah yang berjauhan adalah jarang sekali terjadi. Mereka juga beranggapan
bahwa pada hakekatnya manusia tidak cenderung menciptakan hal-hal baru dan
lebih suka meminjam saja penemuan-penemuan dari kebudayaan orang lain lebih
daripada menciptakan unsur budaya sendiri. Sama halnya pada aliran
Jerman-Austria yang sams-sama beranggapan bahwa manusia lebih suka meminjam
kebudayaa lain. Karena dasarnya manusia itu bukan pencipta ide baru.[3]
C. Fungsionalisme
Tokoh utama teori ini adalah Bronislaw Malinowski yang
memiliki anggapan atau asumsi bahwa setiap unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat
di mana unsur terdapat atau dapat dikatakan bahwa pandangan fungsionalisme
terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah
menjadi kebiasaan.[4]
Pemikiran Bronislaw Malinowski mengajukan beberapa unsur pokok kebudayaan
yang meliputi, sebagai berikut:[5]
· Sistem normatif yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara
para anggota masyarakat agar dapat menguasai alam di sekelilingnya.
· Organisasi ekonomi
· Mechanism and Agencies of education yaitu alat-alat dan lembaga-lembaga
atau petugas untuk pendidikan. Misalnya keluarga, karena keluarga adalah
berperan sebagai lembaga awal dalam mengajarkan pendidikan sebelum memasuki
dunia pendidikan.
· Organisasi kekuatan (the organization of force). Bronislaw Malinowski
sebagai penganut teori fungsional selalu mencari fungsi atau kegunaan setiap
unsur kebudayaan untuk keperluan masyarakat.
D. Fungsionalisme-struktural
Sama halnya Bronislaw Malinowski yang menjadi tokoh utama
dalam aliran fungsionalisme, dalam aliran fungsionalisme-struktural yang tokoh
utamanya adalah Arthur Reginald
Radcliffe-Brown. Yang sama-sama alhli lain dalam antropologi sosial mendasarkan
teorinya mengenai perilaku manusia pada konsep fungsionalism. Tetapi ada
perbedaan sudut pandang bahwa berbagai aspek perilaku sosial, bukanlah
berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tapi justru timbul untuk mempertahankan
struktural sosial masyarakat.
Satu contoh kongkret dari pendekatan yang bersifat struktural-fungsional
dari Radcliffe-Brown adalah analisa tentang cara penanggunlangan mengenai
ketegangan yang kecenderungan timbul di antara orang-orang yang terikat karena perkawinan, yang terdapat
dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda.Satu masalah terbesar dari
pendekatan teori fungsional strutural ini, adalah sulitnya untuk menentukan
apakah satu kebiasaan tertentu pada nyatanya berfungsi dalam arti membantu
pemeliharaan sistem sosial masyarakat.[6]
E. Strukturalisme
Dari sudut pandang Claude Levi-Strauss sebagai tokoh
terkemuka dari pendekatan analisa kebudayaan yang dinamakan Struktural Perancis. Struktural Levi-Straus
berbeda dengan Struktural Racdcliffe-Brown,karena
permasalahn yang menjadi perhatian utama dari Brown adalah elemen yang
bagaimanakah yang berfungsi dalam masyarakat, sedangkan Levi-Straus lebih
konsentrasi pada asal-usul dari sistem dan selalu memandang sebagai kebudayaan.
Seperi halnya adanya upacara-upacara dan pola kehidupan sehari-hari.[7]
Antropologi Levi-Straus juga bertujuan untuk menemukan
model-model bahsa dan budaya melalui struturnya yaitu pemahaman terhadap
pikiran dan perilaku kehidapan manusia .[8]
F. Etnosains
Etnosains
dapat dikatakan sebagai suatu susunan bahasa. Bila dalam pendekatan
struktural dari Levi-Straus dimasukkan aturan-aturan mengenai cara berfikir
yang mungkin melatar belakangkan suatu kebudayaan dalam antropologi pastinya
memunculkan etnografi dalam kebudayaan di
masyarakat, dalm suatu pendekatan etnografis yang baru diberi nama ethosciece,
aturan-aturan demikian dicoba dirumuskan berdasarkan analisa logis dan data
etnografis dan kemungkinan bahwa analisa itu
berpendapat jika dapat diungkapkandiwarnai oleh penilaian sepihak dari
peneliti.
Banyak pengikut ethnoscience berpendapat jika dapat
diungkapkan aturan-aturan yang menjadi dasar dari perilaku budaya yang tepat, maka
banyak hal yang dilakukan oleh manusia dan alasan mengapa dia berlaku seperti itu, seperti
halnya dengan tata bahasa yang tidak menjelaskan mengapa suatu bahasa memiliki
sifat-sifat yang ada dan bagaimana
proses perubannya.[9]
A. Simbolik
Geertz adalah seorang pakar Antropologi Amerika
yang memperkenalkan perspektif baru di bidang antropologi untuk melengkapi
beberapa perspektif sebelumnya, yaitu aliran struktural fungsional yang
berkembang di Inggris melalui tokoh-tokohnya, seperti Bronislaw Malinowski dan
Redelife Brown. Dan juga aliran evolusionis yang berkembang lebih dahulu
sebelum aliran, struktural-fungsional memperoleh pengakuan akademis, dengan
tokohnya, seperti Frazer, Tylor, dan Marert.
Di Amerika, aliran struktural fungsional berkembang berkat karya Turner yang
merupakan guru Clifford Geertz. Meskipun kemudian terdapat perbedaan di dalam
perspektif antropologinya.Jika Turner lebih mengarah ke antropologi sosial
sebagaimana aliran ini berkembang di Inggris, maka Geertz lebih masuk ke dunia
budaya atau kajian antropologi budaya, terutama kajian-kajian tentang dinamis
hubungan antara agama dan budaya.Di antara karya itu adalah the Religion of
java,Islam Observed, dan karya lain misalnya Religion as aCultural
System.
Perspektif simbolik memang menjadi lahan baru di tengah berbagai aliran yang
sudah ada sebelumnya dan dirasakan mengalami kejenuhan. Akan tetapi, perspektif
ini sebagai kelanjutan tidak langsung dari perspektif
fenomenologi-interpretatif di dalam kajian-kajian agama memiliki “kesamaan”,
yaitu ingin memahami apa yang ada di balik fenomena. Ia tidak berhenti pada
fenomena saja, tetapi bergerak menatap lebih mendalam pada dunia fenomena yang
sering dikonsepsikan sebagai pemahaman interpretatif.
Kebudayaan dalam Perspektif
Antropologi Simbolik
Kebudayaan adalah istilah yang kompleks.Begitu kompleksnya sehingga terdapat
sangat banyak definisi tentang kebudayaan itu. Kluckholn, misalnya telah
melakukan pelacakan terhadap sekian banyak pengertian tentang kebudayaan dan
kemudian merangkumnya menjadi:
(1) Keseluruhan cara
hidup suatu masyarakat,
(2) Warisan sosial
yang diperoleh individu dari kelompoknya,
(3) Suatu cara
berpikir, merasa, dan percaya,
(4) Suatu abstraksi
dari tingkah laku,
(5) Suatu teori pada
pihak antropologi tentang cara suatu kelompok masyarakatnyatanyabertingkah
laku,
(6) Suatu gudang
untuk mengumpulkan hasil belajar,
(7) Seperangkat
orientasi-orientasi standar pada masalah yang sedang berlangsung,
(8) Tingkah laku
yang di pelajari,
(9) Suatu mekanisme
untuk penataantingkah laku yang bersifat normative,
(10) Seperangkat teknik
untuk menyesuaikan, baik dengan linkungan luar maupun dengan orang-orang lain
(11) Suatu endapan
sejarah.
Di dalam menidefinisikan kebudayaan, ahli
antropologi simbolik tampaknya berbeda dengan aliran evolusionis yang
mendefiniskan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia atau
kelakuan dan hasil kelakuan.Oleh karena itu, dalam perspektif simbolik,
kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai
pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia.Kebudayaan adalah
pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
tersebut.
Kebudayaan,
dengan demikian ialah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia
sebagaian pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai mahkluk sosial, yang
isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif
dapat digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan yang
dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukannya.
Kebudayaan dalam konsepsi ini mengandung dua unsure utama, yaitu sebagai pola
bagi tindakan dan pola dari tindakan. Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan
ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara
selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan
tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai
pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh
manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya atau dlam pengertian lain
ialah sebagai wujud tindakan.
Secara cukup
konsisten, Geertz meeberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen,
yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan
sebagai sistem nilai.Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi pola
dari atau model of, sedangkan sistem nilai ialah representasi dari pola
bagi atau model for. Jika “pola dari” adalah representasi kenyataan
sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka “pola bagi” ialah
representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan
tindakan itu contoh yang lebih sederhana adalah upacara keagamaan yang
dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang
diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara
keaagamanadalah pola bagi atau model untuk.
Akan tetapi,
kemudian mucul persoalan teoritis, bagaimana menghubungkan antar pola dari dan
pola bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara
bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau
menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makana.Oleh karena
itu, secara cermat Geertz melihat hal itu terletak pada sistem simbol.Simbollah
yang memungkinkan manusia menagkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan
dunia pengetahuan.Jadi, menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari
tiga hal uatama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai
atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau
interpretasi. Adapun titik pertemuan
antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol ialah yang dinamakan makna (system
of meaning).Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah
symbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai
menjadi pengetahuan.
Untuk memahami
budaya, seorang pengkaji tidaklah berangkat dari pikirannya sendiri, tetapi
harus berdasar atas apa yang diketahui, dirasakan, dialami oleh pelaku budaya
yang dikajinya atau disebut sebagai From The Native Point’s of View,
yang merupakan hakikat dari pemahaman antropologis. Semenjak Malinowski,
perdebatan metodologis mengenai dari mana memandang kebudayaan manusia telah
dilakukan sehingga muncul istilah-istilah: perspektif “dalam” versus “luar”,
deskripsi “orang pertama” versus “orang ketiga”, teori “phenomenology” versus
“objektivistik”, atau teori “kognitif” versus “behavioral”, analisis “emic”
versus “etik” yang memebela terhadap pemilihan ilmu-ilmu sosial, termasuk
antropologi. Di dalam kerangka ini, Geertz mengambil posisis yang disebutnya
sebagai, “melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku”.
Dalam konteks ini, kenyataan harus memaparkan apa yang dipahami oleh pelaku
budaya maka berakibat terhadap pemaparan berbagai ungkapan tersebut secara
panjang lebar, yang disebut sebagai thick description, atau deskripsi
tebal yang berlawanan dengan thin description, yang disebut deskripsi
ringkas. Lukisan mendalam yang dikerjakan oleh etnografi itu dalam sudut
pandang buku teks ialah menerapkan hubungan, menyeleksi informan, mentranskip
teks-teks, mengambil silsilah-silsilah, memetakan sawah-sawah, mengisi sebuah buku
harian, dan sebagainya.
Berangkat dari konsepsi tersebut, tulisan Geertz dalam beberapa karyanya
merupakan pemaparan panjang lebar sebagai hasil wawancara mendalam atau
observasi terlibat sehingga dapat menggambarkan secara mendalam berbagai peristiwa
dan berikut makna-makna yang terkandung di dalamnya.Di dalam tulisannnya
mengenai “Abangan, Santri, Priayi dalam Mayarakat Jawa” dan “Islam yang Saya
Amati” lukisan mendalam sebagai sebuah deskripsi di dalam antropologi
interpretatif itu sangat kentara.[10]
B. Interprentivisme
Paradigma interpretivismemenekankan cara pandang, pemahaman dan makna.Dalam
manajemen pendidikan, interpretifisme berada pada bagaimana pendidikan
diperoleh di managemen sedemikian rupa agar mencapai tujuannya. Contoh yaitu:
fenomena UAN yang meresahkan hampir semua civitas akademik mulai dari siswa
orang tua sampai pada perangkat sekolah, yang menuntut para guru untuk selalu
bekerja keras agar murid-muridnya lulus dengan nilai yang memuaskan. Dengan
cara memanajemen pendidikan maka “panekanan” terhadap siswa utuk lulus akan
semakin besar dengan tidak menggunakan rekayasa-rekayasa dalam pendidikan.[11]
C. Postmodernisme
Istilah Postmodernisme dipopulerkan oleh para seniman,
penulis, dan kritikus sastra yang menunjukkan sebuah gerakan yang menolak
modernisme berhenti dalam birokrasi.Dalam
bidang filsafat, Postmodernisme berarti
kritik-krtik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi dan ideologi-ideologi
modern. Dengan kata lain, istilah postmodernisme di bidang filsafat menunjuk
pada segala bentuk refleksi kritik atas paradigma-paradigma modern dan
metafisika pada umumnya. Bahasa dan sastra adalah salah satu cara untuk
mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek utama dalam Hermeneutika. Hermeneutika
menurut Gadamer adalah sebuah refleksi kritis atas cara-cara kita memahami
dunia dan atas bentuk-bentuk pemahaman itu. Menurutnya, bahasa adalah cara yang
khas dari manusia di dunia ini.
Menurut Pauline Rosenau (1992 dalam
Ritzer, 2007) postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya
memenuhi janji-janjinya. Juga
postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan
modernitas.Yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban Barat adalah
industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam
jalur cepat. Namun mereka meragukan prioritas-prioritas modern seperti karier,
jabatan, tanggung jawab personal, birokrasi, demokrasi liberal, toleransi,
humanisme, egalitarianisme, penelitian objektif, kriteria evaluasi, prosedur
netral, peraturan impersonal dan rasionalitas. teoritisi postmodern cenderung
menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia (world view),
metanarasi, totalitas, dan sebagainya.
Dalam bukunya Mengenal Posmodernisme : for begginers,
Appignanesi, Garrat, Sardar, dan Curry (1998) mengatakan bahwa postmodernisme
menyiratkan pengingkaran, bahwa ia bukan modern lagi. Postmodernisme, pada
hakikatnya, merupakan campuran dari beberapa atau seluruh pemaknaan hasil,
akibat, perkembangan, penyangkalan, dan penolakan dari modernisme.
Postmodernisme adalah kebingungan yang berasal dari dua teka-teki besar, yaitu
:
Ia melawan dan mengaburkan pengertian postmodernisme. Ia menyiratkan
pengetahuan yang lengkap tentang modernisme yang telah dilampaui oleh zaman
baru, Sebuah zaman, zaman apapun, dicirikan lewat bukti perubahan sejarah dalam
cara kita melihat, berpikir, dan berbuat. Kita dapat mengenali perubahan ini
pada lingkup seni, teori, dan sejarah ekonomi.
Adapun ciri-ciri dalam aliran antropologi teori postmodernisme, terdapat delapan karakter sosiologis
postmodernisme yang menonjol, yaitu :
1.Timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek
modernitas,
memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden , dan diterimanya pandangan
pluralisme relativisme kebenaran.
2.Meledaknya industri media massa, sehingga ia bagaikan
perpanjangan dari sistem indera, organ dan saraf kita, yang pada urutannya
menjadikan dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media massa
telah menjelma bagaikan “agama” atau “tuhan” sekuler, dalam artian perilaku
orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari
telah diatur oleh media massa, semisal program televisi.
3.Munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini
muncul diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin meragukan
terhadap kebenaran sains, teknologi dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi
janjinya untuk membebaskan manusia, tetapi sebaliknya, yang terjadi adalah
penindasan.
4.Munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan
apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu.
5.Semakin menguatnya wilayah perkotaan (urban) sebagai pusat
kebudayaan, dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga
berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atas negara berkembang.Ibarat
negara maju sebagai “titik pusat” yang menentukan gerak pada “lingkaran
pinggir”.
6.Semakin terbukanya peluang bagi klas-klas sosial atau
kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era
postmodernisme telah ikut mendorong bagi proses demokratisasi.
7.Era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya
kecenderungan bagi tumbuhnya eklektisisme dan pencampuradukan dari berbagai
wacana, potret serpihan-serpihan realitas, sehingga seseorang sulit untuk ditempatkan
secara ketat pada kelompok budaya secara eksklusif.
8.Bahasa yang digunakan dalam waacana postmodernisme
seringkali mengesankan ketidakjelasan makna dan inkonsistensi sehingga apa yang
disebut “era postmodernisme” banyak mengandung paradoks
Terdapat banyak contoh kasus dalam
sosial budaya Indonesia yang dianggap sebagai suatu sifat atau kegiatan
postmodern dalam sudut pandang kaum postmodern itu sendiri.Misalnya dari media
elektronik, berupa televisi. Bentuk iklan rokok A mild menggunakan filsafat
posmodern yang terlihat dari tema-tema yang sering diajukan terkesan sangat
tidak berhubungan dengan produknya, malah lebih sarat dengan tema politik dan
sosial yang sedang berkembang. Seperti sebelumnya, tagline ‘talk less do more’
yang menyindir kepada orang – orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak ada
tindakan , atau tagline ‘tanya kenapa’ juga menyindir pendidikan di Indonesia,
begitu juga dengan tagline ‘ wani piro’ yang menyindir para koruptor dan
penyuap. Selain itu bentuk dekonstruksi dan hyperealis dapat kita temukan dalam
internet dan game online, yang kini sangat digandrungi oleh masyarakat
khususnya kaum muda-mudi.Facebook yang merupakan bentuk network engine (sarana
mencari teman di dunia maya yang difasilitasi dengan foto diri, testimonial/pendapat
dari teman-temannya, buletin board yang berfungsi sebagai papan pengumuman
telah menjadi rumah kedua dalam masyarakat untuk bersosialisasi secara
maya.Foto yang ditampilkan merupakan aspal (asli tetapi palsu), walau ada
sebagaian yang memasang dengan foto yang asli.,chatting : kenal di dunia maya tetapi belum tentu kenal di dunia
nyata. Selain itu bentuk desain poster/pamflet ataupun media promosi lainnya,
yang ada kini sering berkesan berantakan, asal , atau mungkin mengambil dari
masa lalu.
IV.
KESIMPULAN
Kebudayaan bukanlah sesuatu
yang statis, melainkan bisa mengalami perubahan secara lambat tetapi pasti atau
yang dikonsepsikan sebagai perubahan evolusioner. Perubahan kebudayaan tersebut
terkait dengan proses masuknya berbagai macam kebudayaan dri tempat, suku, dan
ras lain atau juga karena proses sosial yang terus berubah. Teori-teoi diatas
mengajak kita utuk merefleksikan kembali tata nilai kebudayaan yang sekian
waktu lupa dari perhatian masyarakat kita memperenalkan teori sekaligus aplikasinya
pada ranah sosial untuk dianalisis sebagai jembatan kekosongan ruang makna
kebudayaan.
DAFTAR PUSTA
Syam, Nur.
2012. Mazhab-Mazhab Antropoogi.
Yogjakarta: LKIS Printing Cemerlang.
Ihromi. 2006. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
http//www.amarsuteja.blogspot.com/2013/11/15/aliran evoluisonisem//html
http//www.rdwapril_maklh.blogspot.com/2013/15/10/prekfektif
simbolik//html
http//www.bowilampard8.blogspot.com /2011/07/13/ aliran struktural
perancis//html
http://nashir6768.multiply.com/j rnal/item/10/08/09/Struktural.html
[1] Ihroni,I.T.O. Pokok Pokok
Antropologi, Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia,2006. Hlm 49 dan 50.
[2] Ibid., hal.56 dan hal. 57
[4] Ibid., hal 61
[5] http//www.rdwapril_maklh.blogspot.com/2013/15/10/aliran
/fungsional/. Diaksespada tanggal 09 oktober 2014 hari kamis
[6] Ihromi. Hal 61
[8] http://nashir6768.multiply.com/j rnal/item/10/08/09/ stuktural/ diakses pada tanggal 12 oktober 2014 hari senin
[9] Ibid., hal 67 dan hal 68
[10] http//.rdwapril_maklh.blogspot.com/2013/15/10/prekfektif
simbolik.html./diakses pada tanggal 10 oktober 2014 pada hari jumat
[11] http://muhathowil.blogspot.com/2011/11/aliran-positivisme-interpretivisme.html/ diakses pada tanggal 8 oktober 2014 pada
hari rabu





0 Response to "TEORI TEORI DALAM ANTROPOLOGI"
Post a Comment